
Insentif Pajak Minus SHU
Setelah pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Juni silam, perjuangan panjang eksponen gerakan koperasi agar SHU tidak dipajaki, belum berakhir.
Seperti diketahui, poin utama dari aturan tersebut adalah turunnya tarif pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. PP yang diluncurkan Presiden ini sekaligus sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, di mana aturan baru ini efektif berlaku mulai 1 Juli 2018.
Ketentuan dalam PP 23/2018 mengatur pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang peredaran bruto atau omzetnya sampai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Adapun ketentuan pertama, penerapan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulan.
Regulasi tersebut juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif pajak penghasilan final di mana wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun; wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun; dan wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun.
Adapun tujuan PP 23/2018 adalah untuk mendorong pelaku UMKM semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik. Direktorat Jenderal Pajak juga berharap, melalui beban pajak yang lebih ringan, pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya dan melakukan investasi.
Pada 28 September lalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menggelar kuliah umum bertema: "Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang PPh Final UMKM". Hadir Direktur Perpajakan Internasional Prof Dr John Hutagaol, yang juga Ketua IAI KAPj, sebagai narasumber.
"PP No. 23 Tahun 2018 merupakan suatu paket insentif pajak bagi UMKM, oleh karena itu sifatnya pilihan atau optional. WP UMKM dapat memilih untuk menerapkan PPh Final 0,5% atau lebih memilih ketentuan umum" papar John.
Menurut John, PP No. 23 Tahun 2018 ada unsur mendidiknya karena WP dapat menikmati fasilitas UMKM selama 7 tahun, dan setelah itu mengikuti ketentuan umum. Demikian pula bagi WP badan korporasi dan WP badan non korporasi jangka waktunya masing-masing 3 tahun dan 4 tahun, setelah itu pemenuhan kepatuhannya berdasarkan ketentuan umum.
"Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 setelah batas waktu fasilitas berakhir, selanjutnya diharapkan WP naik kelas (entering the new level) dalam pemenuhan kepatuhannya,” imbuh John.
Sementara itu dalam pandangan Darussalam , Managing Partner DDTC, penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 Tahun 2013 tentangPajak Penghasilan (PPh) Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau sering disebut sebagai PPh Final yang ditujukan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adanya beleid tersebut bukan tanpa alasan.
Sebagaimana telah diketahui, UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, baik pertumbuhan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan tren yang selalu positif selama 1 dekade terakhir. Sayangnya, kontribusi tersebut kurang tercermin dalam aspek perpajakan. Sebagai ilustrasi, menurut bahan sosialisasi dari Ditjen Pajak, di tahun 2017 penerimaan PPh Final UMKM hanya berkisar 2,2% dari total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Penting untuk dicatat bahwa PP No.23 Tahun 2018 tidak merujuk pada definisi UMKM menurut aset, omzet, jumlah tenaga kerja, dan permodalan seperti yang telah diatur oleh UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penyebutan istilah ‘UMKM’ dalam beleid ini diasosiasikan pada wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah yakni suatu kelompok masyarakat dengan daya pikul beban pajak tertentu. Oleh karena itu, walau PP N0. 23 Tahun 2018 kerap disederhanakan menjadi PPh Final bagi UMKM, namun konteksnya berbeda dengan pengertian UMKM yang berlaku umum.
Menyikapi tingginya potensi penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan yang rendah, bagaimanakah terobosan kebijakan pajak yang dapat diterapkan atas pelaku di sektor UMKM? Di sisi lain, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kemandirian UMKM?
UMKM dapat dikatakan sebagai hard-to-tax sector, yang berarti kepatuhan para wajib pajak di sektor tersebut tidak mudah untuk diawasi. Hard to tax sector umumnya juga sulit dijangkau oleh sistem pelaporan atau penyetoran yang berlaku secara umum (Bahl, 2004). Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakmampuan UMKM dalam melakukan administrasi pembukuan yang baik sehingga penghasilan neto pemain di sektor UMKM sulit untuk dapat diketahui secara pasti.
Di banyak negara, terobosan yang kerap dipergunakan untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan penerapan presumptive tax. Presumptive tax merupakan cara menghitung nilai pajak terutang dengan indikator selain penghasilan neto, yang dinilai dapat mencerminkan penghasilan wajib pajak tertentu. Tujuannya jelas, yaitu memberikan kemudahan administrasi, mengurangi biaya kepatuhan, efektivitas penerimaan, serta perluasan basis pajak (Thuronyi, 1996).
Pada umumnya, indikator selain penghasilan neto yang dipergunakan sebagai basis pajak merujuk pada indikator yang tidak rentan dimanipulasi serta membuat wajib pajak yang bersangkutan lebih mudah diamati kepatuhannya (Slemrod dan Yitzhaki, 1996). Dalam rangka memberikan kesederhanaan administrasi (simplification), nilai peredaran bruto menjadi basis pajak yang popular dipergunakan dalam rezim presumptive tax (Bird dan Wallace, 2003).
Sebagian akademisi menganggap bahwa presumptiv tax lebih memprioritaskan kemudahan administrasi sehingga kurang merefleksikan ability to pay yang mengurangi keadilan dalam sistem pajak (Logue dan Vettori, 2010). Akan tetapi, kemudahan administrasi nantinya dapat menjamin partisipasi yang lebih luas. Secara tidak langsung, meningkatnya partisipasi justru mendukung distribusi beban pajak yang lebih merata sehingga sistem pajak tidak akan ditopang oleh wajib pajak yang ‘itu-itu saja.’ Dengan demikian, presumptive tax merupakanalternatif yang tepat bagi pemajakan atas UMKM di Indonesia.
Keunggulan PP No. 23 Tahun 2018
Masih menurut Darussalam, di Indonesia presumptive tax, dalam konteks UMKM, telah diterapkan melalui pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dengan pembebanan tarif sebesar 1% atas peredaran bruto hasil usaha. Sasarannya adalah wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang memiliki omzet usaha dalam satu tahun tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. Beban pajak yang rendah serta kesederhanaan administrasi diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.
Sayangnya, PP 46 Tahun 2013 masih mengandung beberapa permasalahan. Utamanya mengenai insentif bagi UMKM untuk tetap ‘bertahan’ dengan menggunakan sistem PPh Final dalam waktu yang permanen. Tarif yang rendah dan sistem yang mudah justru berpotensi menciptakan keengganan UMKM untuk mulai menyelenggarakan pembukuan dengan baik serta tunduk terhadap sistem PPh yang berlaku secara umum. Akibatnya, upaya untuk mengikis informalitas dari sistem pajak menjadi sulit untuk diwujudkan.
Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 yang turut mengatur mengenai adanya batasan waktu (grace period) bagi penerapan PPh Final bagi wajib pajak tertentu. Batasan waktunya berdurasi antara tiga hingga tujuh tahun yang dibedakan berdasarkan karakteristik UMKM. Melalui batasan waktu tersebut, penerapan PPh Final bersifat sementara (temporary) dan wajib pajak UMKM didorong untuk mempersiapkan pembukuan untuk menghitung kewajiban pajaknya.
Tidak hanya itu, insentif bagi keterlibatan pelaku UMKM yang saat ini masih berada di luar radar otoritas pajak juga semakin besar. Hal ini ditunjukkan dari penurunan tarif, dari 1% menjadi 0,5% terhadap peredaran bruto. Dengan demikian, berbagai tujuan dari presumptive tax yaitu kesederhanaan, meningkatkan kepatuhan, keberpihakan pada pengembangan bisnis UMKM, sekaligus menjaring partisipasi yang lebih luas dari UMKM ke dalam sistem PPh telah tercermin dalam beleid ini.
Tugas yang masih tersisa adalah bagaimana peran pemerintah, khususnya otoritas pajak, dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait sistem pembukuan dan aspek administrasi pajak. Berbagai upaya tersebut sejatinya guna memastikan UMKM yang berada dalam rezim presumptive untuk dapat bersiap memasuki rezim PPh yang berlaku umum pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Kebutuhan pelaku UMKM terhadap edukasi mengenai aspek perpajakan dalam kegiatan usahanya merupakan sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah (IDB, 2009).(PRIONO/FOTO ISTIMEWA)

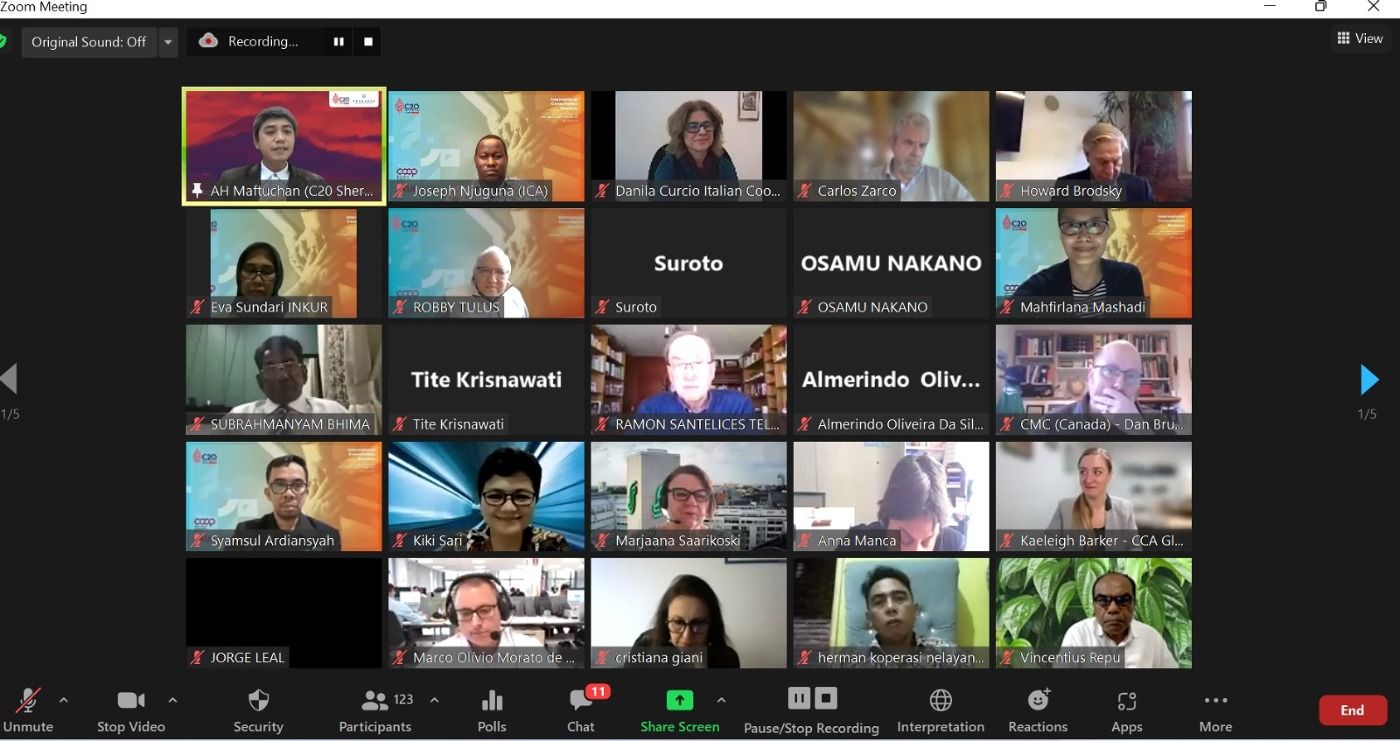







Komentar