
"Problematika Sertifikasi Tanah di Kalangan Koperasi Indonesia, " Rumah Bersama" Nirsertifikat"
Ada fakta ironis yang tak banyak publik ketahui. Lebih dari 130 ribu koperasi di Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan aset dan bisnis yang bergulir, ternyata berdiri di atas tanah nirsertifikat. Mengapa bisa begitu?

Prof.Dr.Ahmad Subagyo, Wakil Rektor III IKOPIN University, mengeja fenomena di atas dalam pengandaian ironis Koperasi versus Sertifikat Hak Milik (SHM) ibarat kisah "Rumah Bersama" yang tak bisa punya sertifikat.
Bayangkan, 50 warga desa patungan membeli tanah untuk mendirikan koperasi. Lahan itu akan jadi gudang bersama, tempat pelatihan, atau pusat pemasaran hasil pertanian. Tapi ketika mengurus sertifikat, jawaban negara selalu sama: "Koperasi tak boleh punya SHM!"
Problematika ini diurai Ahmad Subagyo, dalam naskah akademiknya. Menurutnya, akar masalah tersebut ada pada struktur keuangan koperasi yang ambigu, terutama konsep "simpanan" (pokok dan wajib). Simpanan anggota bisa ditarik kapan saja, membuat kepemilikan aset koperasi dianggap tidak permanen oleh hukum.
"Bagaimana negara mau percaya beri SHM, jika modal koperasi bisa lenyap saat anggota memutuskan keluar?" tulis Subagyo.
Teori Margaret Land: Koperasi Butuh Ekuitas yang Demokratis dan Permanen
Di sinilah pemikiran Margaret Land, pakar keuangan koperasi global, relevan. Dalam bukunya Cooperative Equity and Ownership (2013), Land menegaskan:
"Koperasi harus membangun ekuitas yang demokratis, di mana kontribusi anggota sejalan dengan manfaat yang diterima, tetapi tetap stabil untuk menjamin keberlanjutan usaha."
Land menyarankan model "irredeemable shares" (saham tak bisa ditarik) dan "base capital plan":
Saham Permanen: Simpanan pokok diubah jadi saham tetap. Anggota tak bisa menariknya, mirip saham di PT.
Alokasi Laba Berbasis Patronase: Laba koperasi dibagi sesuai transaksi anggota, bukan jumlah modal.
Revolusi Ekuitas: Dana dikembalikan ke anggota secara bertahap, bukan sekaligus.
Ketika Prof. Dr. Ahmad Subagyo mencermati ihwal peliknya koperasi di Indonesia dalam mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah.
Subagyo mengajak kita merenungkan sesuatu yang sangat mendasar: bagaimana negara memandang kekuatan dan keberlanjutan koperasi sebagai rumah bersama.
Dalam naskahnya, Prof. Subagyo menggambarkan koperasi seperti kapal besar yang mengangkut harapan banyak orang. Sayangnya, kapal ini belum juga dipercaya negara untuk memiliki “surat kepemilikan kapal” berupa SHM tanah. Mengapa demikian?
Kuncinya terletak pada struktur keuangan koperasi yang, menurut Prof. Subagyo, masih ambigu. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-dua istilah yang di permukaan tampak kokoh, namun sebenarnya sangat cair.
Anggota bisa menarik simpanan mereka kapan saja. Akibatnya, negara melihat koperasi sebagai entitas yang “bisa bubar sewaktu-waktu”, bukan institusi yang kukuh dan layak diberi hak milik atas tanah.
Bandingkan dengan yayasan yang asetnya abadi karena berbasis wakaf, atau perseroan terbatas (PT) yang modalnya berupa saham tetap dan hanya bisa berpindah lewat mekanisme yang jelas. Di koperasi, jika anggota keluar massal dan menarik simpanan, siapa pemilik tanahnya? Inilah pertanyaan yang membuat negara ragu.
Di sisi lain, praktik di lapangan pun seringkali “mengakali” regulasi. Ada koperasi yang meminjam nama ketua atau pengurus untuk mengurus SHM, namun ini justru berisiko hukum karena bertentangan dengan prinsip legalitas subjek hukum tanah di Indonesia. Negara pun semakin waspada dan enggan memberikan SHM kepada koperasi yang status ekuitasnya labil.
Namun, benarkah tidak ada jalan keluar? Di sinilah pemikiran Margaret Lund, pakar koperasi dari University of Wisconsin, menjadi sangat relevan. Dalam buku “Cooperative Equity and Ownership”, Lund menegaskan bahwa kekuatan koperasi bukan sekadar pada kumpulan simpanan, melainkan pada bagaimana ekuitas itu dikelola secara demokratis dan berkelanjutan.
Equity koperasi, menurut Lund, adalah hasil kontribusi anggota yang dikelola bersama, dikontrol secara demokratis, dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif anggota, bukan untuk keuntungan segelintir orang.
Lund juga menyoroti pentingnya “modal yang sabar” (patient capital) dalam koperasi-modal yang tidak mudah ditarik, sehingga koperasi punya daya tahan jangka panjang.
Banyak koperasi di dunia, seperti CROPP Cooperative di Amerika, menerapkan model ekuitas permanen: anggota wajib menanamkan modal yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, dan imbal hasil diberikan dalam bentuk manfaat atau patronage, bukan dividen besar seperti di PT. Dengan model seperti ini, koperasi mampu membangun kepercayaan bank, pemerintah, bahkan masyarakat untuk mengelola aset besar, termasuk tanah.
Tawaran Solusi : Reformasi Struktur Ekuitas Koperasi
Dari sini, Prof. Subagyo menawarkan solusi : koperasi Indonesia perlu mereformasi struktur ekuitasnya. Simpanan pokok dan wajib bisa dikonversi menjadi “saham koperasi” atau ekuitas permanen yang tidak bisa diambil kapan saja. Dengan begitu, koperasi akan tampil sebagai institusi yang layak dipercaya negara untuk memiliki SHM, persis seperti PT atau yayasan. Negara pun punya alasan kuat untuk mengubah regulasi dan memberi akses SHM kepada koperasi yang sudah membuktikan kekuatan ekuitas dan tata kelola demokrasinya.
Jadi, masalah SHM bagi koperasi bukan sekadar soal administrasi pertanahan, tapi soal kepercayaan negara pada daya tahan koperasi sebagai rumah bersama. Jika koperasi berani berbenah mengikuti prinsip equity ala Margaret Lund-membangun ekuitas yang demokratis, stabil, dan berjangka panjang-maka tak ada alasan lagi bagi negara untuk menahan SHM dari tangan koperasi. Inilah saatnya koperasi Indonesia naik kelas, dari sekadar “rumah kontrakan” menjadi “rumah milik bersama” yang kokoh dan abadi. (*)







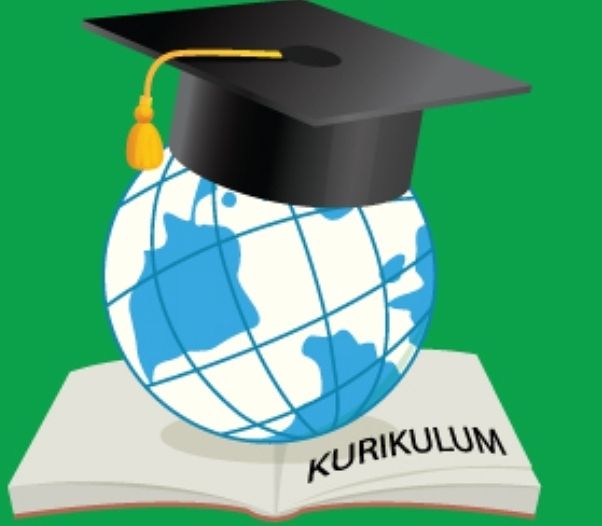

Komentar